Tantra Nur Andi
Borneo Tribune, Pontianak
Dampak paling besar adanya ketidakadilan gender pada perempuan adalah adanya pandangan perempuan berada pada warga kelas dua sehingga tidak punya akses terhadap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Demikian diungkapkan Direktur Gemawan, Laily Khairnur Minggu (9/3).
Kondisi ini, kata Laily sering terjadi baik dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dan negara. Contohnya saat menentukan sebuah keputusan, sering seorang istri akan mengikuti keputusan yang diambil oleh suaminya dalam menentukan kebijakan rumah tangga mereka. Dalam masyarakat, perempuan tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan arah perencanaan strategis kebutuhan dan masa depan desa. “Paling banter perempuan hanya mengurusi konsumsi pertemuan,” katanya.
Sehingga kebijakan yang diambil untuk tata kehidupan desa, tidak melibatkan kepentingan dan kebutuhan perempuan yang merupakan penduduk desa tersebut. Dan terkesan apa yang didapatkan oleh penduduk perempuan hanya merupakan “hadiah kebaikan hati” dari pihak pengambil keputusan di tingkat desa yang notabene adalah laki-laki.
Pada tingkatan yang lebih luas misalnya dalam kebijakan tata kehidupan pemerintahan dan bernegara. Banyak keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan publik kadang-kadang sangat merugikan perempuan. Contoh kebijakan KB, Kenaikan BBM dan kebijakan lainnya. ”Kita tahu bagaimana kampanye pemerintah tentang KB yang katanya untuk menekan pertumbuhan penduduk. Pertanyaannya kenapa ini harus dipaksakan hanya kepada perempuan. Padahal banyak risiko yang harus ditanggung oleh perempuan. Kenapa kontrasepsi tidak dipaksakan kepada laki-laki yang mungkin saja risikonya akan lebih kecil. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan yang ada sangatlah didominasi oleh state man minded policy,” ungkapnya.
Bicara soal kebijakan pada wilayah kekuasaan, ujar Laily perempuan tidak bisa menentukan sebuah kebijakan karena secara faktual perempuan tidak punya kekuasaan baik formal maupun informal. Fakta di lapangan porsi keterwakilan perempuan di tingkat Legislatif maupun eksekutif yang posisinya pada level pengambil keputusan (decision maker) sangatlah kecil.
Pada Pemilu 1999 tingkat keterwakilan perempuan secara kuantitatif di DPR-RI hanya mencapai 9, % lebih kecil dibanding pemilu 1997 yang mencapai kira-kira 11%. Keterwakilan ini baru pada tataran kuantitas, belum kualitas. ”Secara kuantitas saja perempuan tidak terwakili bagaimana dengan kualitas,” tanya Laily.
Padahal hampir 51 persen jumlah massa pemilih setiap pemilu adalah perempuan dan sangat ironis jumlah yang besar ini hanya terwakili sebanyak 9 persen. Untuk Kalbar, DPRD provinsi hanya ada 2 orang perempuan dari 54 jumlah keseluruhan. Apalagi di Kabupaten rata-rata hanya ada 1 sampai 2 orang perempuan anggota legislatif. Belum lagi ketidakterwakilan perempuan di level eksekutif. Tidak ada satu pun perempuan Indonesia yang menjadi Gubernur dan hanya ada 5 orang Bupati perempuan dari 331 Bupati yang ada di Indonesia.
Bahkan asumsi yang dibangun menyatakan salah perempuan sendiri yang tidak mau menduduki posisi tersebut padahal peluang sudah ada. Selain itu banyak opini publik mengatakan tidak ada perempuan potensial yang bisa membuat kebijakan publik. Orang yang mempunyai cara pandang demikian adalah orang yang tidak objektif melihat persoalan di lapangan.
Mereka tidak melihat bagaimana sebuah perusahaan akan memberlakukan upah yang tidak sama antara buruh laki-laki dan buruh perempuan atau karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Sebuah institusi atau lembaga akan memilih seorang laki-laki yang beristri daripada seorang perempuan bersuami dan punya anak untuk menduduki jabatan tertentu. Begitu juga partai politik akan selalu meletakkan perempuan pada urutan terbawah dalam mekanisme pencalonan untuk menjadi anggota legislatif. Selalu saja perempuan tidak menjadi prioritas.
”Padahal bicara ketersediaan perempuan sepertinya kita tidak meragukan lagi bagaimana kemampuan dan kiprah mereka dalam berbagai bidang,” paparnya.
Aktivis perempuan Pusat Pemberdayaan Studi Wanita (PPSW) Borneo, Reni mengatakan persoalan perempuan yang paling mendasar di Kalbar adalah persoalan pendidikan terutama didaerah pedalaman. Banyak perempuan yang belum mendapatkan akses wajib belajar sembilan tahun. Karena masih adanya budaya di masyarakat seperti di pedesaan yang menganggap perempuan tidak boleh tahu ini dan itu dan tidak boleh ikut memberikan keputusan bagi dirinya, keluarga, dan bagi masyarakat. Masih adanya budaya pembatasan pada perempuan ini membuat pola hidup perempuan menjadi terbatas. Aturan budaya yang melingkupi perempuan seperti budaya partiarki yang menganggap perempuan hanya bisa bekerja di rumah padahal perempuan memiliki kesempatan yang sama.
”Dan sudah saatnya perempuan berani bicara tentang hak-haknya dan mengangkat eksistensi dirinya,” katanya.
Perempuan juga ingin memperoleh kemajuan setiap saat seperti halnya laki-laki yang sama-sama ingin tumbuh kembang secara maksimal. Tapi perempuan masih belum memperoleh peluang yang sama dalam mengakses pendidikan, ekonomi dan sosial politik. Masalah gerakan perempuan diantaranya, budaya kerja perempuan hanya wilayah domestik dan peran di wilayah publik dibatasi, upah dibayar lebih rendah dari laki-laki, akses ekonomi rendah, minimnya partisipasi pengambilan keputusan.
Keadaan perempuan, kata Reni masih selalu disibukkan dalam menjalani kodrat saat hamil, menyusui, merawat anak-anak dan bekerja mencari nafkah. Meningkatnya kekerasan trafficking di era global juga menambah sejumlah tindak kekerasan. Kesempatan memperoleh akses pendidikan berkualitas di negeri ini masih rendah. Tidak semua anak-anak negeri ini berkesempatan mengenyam pendidikan di sekolah yang maju. Terlebih bagi perempuan miskin, hanya mampu menikmati pendidikan dasar secara gratis dengan fasilitas tidak memadai. Sekolah-sekolah negeri yang didanai dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum menunjukkan pengelolaan sekolah yang profesional. Kualitas sekolah rendah dengan mutu guru-guru belum standar, buku-buku ajar sedikit dan saran prasarana sekolah kurang. Anak-anak miskin bersekolah di dekat rumah mereka di pedesaan dan pegunungan dengan kualitas sekolah yang tidak memadai. Anak-anak sekolah dengan kualitas rendah akan menghasilkan mutu rendah pula. Perempuan berpendidikan rendah, mudah terkooptasi oleh tuntutan adat setempat agar menikah di usia dini.Perempuan dibatasi oleh adat menikah di usia dini, orang tua merasa malu anaknya tidak menikah dari pada tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi. Perempuan dirasa cukup berpendidikan setingkat sekolah menengah SMP/SMU. Bagi orang tua tradisional lebih puas menikahkan anak perempuan mereka, daripada menyekolahkan anak ke pendidikan tinggi. Bagi orang tua, juga tidak menghiraukan bagaimana anak perempuan mereka akan menjalani kehidupan setelah menikah, pekerjaan apa yang akan dilakukan setelah menikah, dan bagaimana mengelola rumah tangga mereka. ”Para anak-anak perempuan miskin yang telah menikah, biasanya tinggal di rumah, dan sebagian lain bekerja sebagai buruh tani atau buruh di pabrik. Keadaan ini memicu tingginya angka perceraian. Kegagalan membangun keluarga, bersumber dari percekcokan masalah keuangan, kesengsaraan berlangsung terus menerus, pembagian peran yang tidak adil, konflik, dan hilangnya komunikasi,” ujarnya.■
Rabu, 26 Maret 2008
Perempuan Dalam Politik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


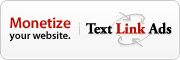
0 komentar:
Posting Komentar